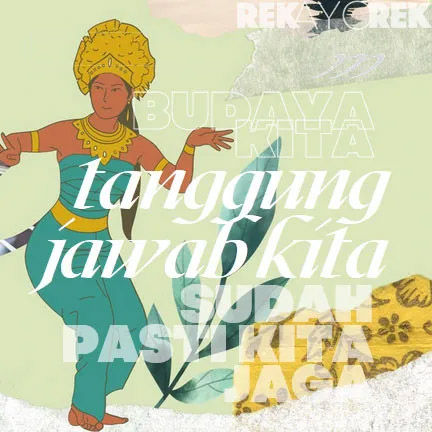Oleh: IM. Sumarsono
Transfer kekuasaan pada 21 Mei 1998 menjadi penanda lahirnya Era Reformasi dengan kesan mendadak dan tidak terencanakan. Krisis ekonomi menjadikan negara Orde Baru yang sebelumnya sangat kuat berubah sebagai negara yang rentan secara ekonomi dan politik. Akibat krisis ini, kelas penguasa mengalami guncangan hebat dan mengalami keretakan. Konsekuensinya, kelas penguasa yang ada rentan oleh perpecahan dan tergantikan oleh kelas penguasa yang lain. Catatan penting dari jatuhnya pemerintahan Soeharto adalah bukan semata-mata disebabkan oleh krisis 1997/1998.
Kacung Marijan (2010: 2-5) mengungkapkan, jika dirunut ke belakang, jatuhnya rezim Orde Baru dan terbukanya demokratisasi adalah puncak akumulasi dari gerakan-gerakan sosial politik menuju demokrasi di tengah himpitan kekuasaan yang otoriter. Kekuatan-kekuatan yang bisa diidentifikasi sebagai civil society, khususnya kekuatan intelektual dan mahasiswa berusaha menyuarakan sesuatu yang lain, yaitu berusaha membuka sistem politik ke arah yang lebih demokrasi.
Para analis berpandangan bahwa keruntuhan penguasa Orde Baru tidak serta merta diiringi oleh proses demokratisasi. Hal ini disebabkan oleh realitas bahwa jatuhnya pemerintahan Orde Baru tidak diiringi oleh kehancuran basis politik pemerintahan Jenderal Soeharto. Malah, sekutu lama Soeharto berhasil mengamankan berbagai posisi strategic dalam pemerintahan baru, sementara rekanan-rekanan bisnis Soeharto masih menjadi faktor menentukan dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia (Hariej 2005: 48, dalam Marijan, 2010: 9). Kecenderungan utama yang membuat Indonesia terjebak dalam sistem politik otoriter sejak akhir 1950-an sampai akhir 1990-an adalah adanya sentralitas kekuasaan yang menguat pada pribadi, kelompok atau institusi (Aspinall 2005; Jackson 1978; Liddle 1985; MacIntryre 1991 dalam Marijan, 2010: 19).
Karena sentralisasi kekuasaan merupakan masalah utama di dalam sistem politik Indonesia pada masa lalu, ketika reformasi politik menguat, para pelaku reformasi berusaha mengatasi masalah ini melalui desain kelembagaan (institusional design) yang ada di lembaga-lembaga politik yang berkaitan dengan kekuasaan dengan gagasan utama adalah bagaimana melakukan pembagian dan pemisahan terhadap lembaga-lembaga yang memiliki kekuasaan.
Jatuhnya rezim Orde Baru menjadi entry point bagi adanya amandemen UUD 45 untuk memuat unsur-unsur konstitusionalisme atas upaya mengontrol kekuasaan. Termasuk di dalamnya adalah membangun adanya mekanisme checks and balances dengan melakukan pengurangan kekuasaan presiden yang diiringi dengan penguatan kekuasaan lembaga perwakilan rakyat (Marijan, 2010: 19-25). Untuk membangun adanya mekanisme cheks and balances, selain dilakukan pengurangan kekuasaan presiden juga diiringi oleh penguatan kekuasaan lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD). Ini untuk mencegah executive heavy sebagaimana terjadi sebelumnya. Implikasi dari perubahan ini menjadikan relasi DPR dan presiden berlangsung seimbang. Dalam pembuatan keputusan-keputusan penting presiden tidak bisa melakukannya sendiri tanpa terlebih dahulu membicarakannya dengan DPR.
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai Presiden keempat Indonesia pada 20 Oktober 1999 atas dukungan Poros Tengah, yaitu gabungan Fraksi Reformasi, Fraksi PPP, FKB, FPBB dan sebagai anggota Fraksi Golkar. Gus Dur kemudian mengumumkan anggota Kabinet Persatuan Nasional yang juga dibentuk melalui kompromi dengan berbagai pihak (Wijayanti, 2002: 1-2). Arbi Sanit (sebagaimana dikutip Wijayanti, 2002) menyebutkan bahwa banyak kalangan partai politik yang seharusnya bermain di luar eksekutif sebagai pengontrol tetapi pada kenyataannya malah masuk di dalamnya. Ini dapat mengancam proses demokrasi. Padahal salah satu agenda terpenting reformasi adalah demokratisasi yang jaminan pentingnya dari sebuah proses demokrasi adalah keberadaan oposisi.
Nurcholish Madjid memberikan support kepada masyarakat dan segenap rakyat agar tidak ragu menjadi oposan terhadap pemerintahan Gus Dur-Mega. Sebab menurutnya, oposisi sama terhormatnya dengan pemerintah, dan akan menjadi kontrol sosial yang efektif. Bagaimanapun kita harus menyelematkan ide dasar dari demokrasi, kata Madjid, yaitu adanya kontrol sosial yang efektif. Menurut Madjid, pemerintah yang berjalan demokratis adalah pemerintah yang memiliki kebebasan, yang berarti diperbolehkannya kritik. Indonesia harus menganut sistem yang bisa mengoreksi dirinya sendiri karena terbuka dan transparan.
Namun, Madjid mengingatkan bahwa keberadaan oposisi di Indonesia itu bukan untuk menjatuhkan presiden “di tengah jalan” sebelum masa kekuasaan pemerintah Gus Dur sesuai konstitusi berakhir. Oposisi menjadi sah untuk menjadi pengimbang dan pengkritik kekuasaan. Secara konstitusional, Gus Dur tidak dapat dijatuhkan meskipun memiliki kekurangan. Karenanya dia mengingatkan agar tidak tergesa-gesa dan jangan sampai mengulangi kesalahan masa lalu. “Kita menganut pemilu periodik dengan sistem presidentil, maka partai oposisi hanya dapat mengganti kekuasaan melalui pemilu mendatang dan bukan menjatuhkan presiden sekarang,” katanya (Dialog Nasional Prospek Politik Oposisi, 2000 dalam HM, 2001; 15-16). Namun, otoritas MPR yang cukup besar —termasuk mengangkat dan memberhentikan presiden— justru terakhir digunakan untuk melakukan proses pemberhentian (impeachment) pada presiden di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Marijan, 2010: 27).
Realitas konfigurasi politik tanpa kekuatan mayoritas di DPR menyebabkan pihak eksekutif harus membangun koalisi dengan partai lain dalam membentuk kabinet. Peneliti LIPI Luky Sandra Amalia (2013) menyebutkan bahwa sejak periode pemerintahan 1999 hingga 2009 tercatat setiap presiden mengakomodir hampir semua parpol untuk menduduki kursi menteri. Kabinet Persatuan Nasional era presiden Abdurrahman Wahid mendapat dukungan 437 kursi yang terdiri dari PKB (51 kursi), Partai Golkar (120 kursi), PDIP (153 kursi), PPP (58 kursi), PAN (34 kursi), PBB (13 kursi), dan Partai Keadilan (7 kursi). Kabinet Gotong Royong masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri melanjutkan pola koalisi yang telah dibentuk oleh Gus Dur namun berkurang tujuh kursi milik Partai Keadilan yang tidak lagi duduk di kabinet.
Hal yang sama juga terjadi pada Kabinet Indonesia Bersatu era presiden SBY yang berhasil meraih dukungan 403 kursi setelah membangun koalisi. KIB memperoleh dukungan 56 kursi dari Partai Demokrat sebagai partai pengusung utama SBY, 11 kursi dari PBB, 45 kursi dari PKS, 1 kursi dari PKPI, 127 kursi Partai Golkar, 58 kursi PPP, 53 kursi PAN, dan 52 kursi PKB.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hampir semua presiden di era reformasi merupakan presiden minoritas (minority president) karena partainya tidak mencapai dukungan mayoritas di DPR. Di sisi lain, koalisi longgar yang dibangun oleh presiden minoritas justru bisa jadi masalah bagi pemerintahan itu sendiri. Seperti halnya yang terjadi pada masa kepemimpinan Gus Dur yang digulingkan dari kursi presiden atas inisiatif partai-partai pendukung pemerintah dan koalisi longgar partai-partai berbasis Islam yang menamakan diri Poros Tengah. Padahal, koalisi ini juga yang mengusung Gus Dur menjadi Presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999.
Meskipun pada era pemerintahan berikutnya tidak terjadi pemakzulan terhadap presiden, kecenderungan yang sama terjadi pada masa pemerintahan Megawati maupun SBY melalui cara lain. Cara yang digunakan oleh DPR adalah melalui penggunaan hak interpelasi atau hak angket DPR. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Presiden Megawati, DPR mengajukan hak interpelasi atas lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan. Hak interpelasi DPR ini juga didukung oleh partai-partai yang kader-kadernya duduk di Kabinet Gotong Royong.
Kejadian yang sama juga menimpa pemerintahan SBY. Dengan demikian, sejak Pemilu 1999 hingga 2009 tidak ada koalisi yang permanen. Pada putaran kedua Pemilu Presiden 2004, misalnya, terbangun koalisi yang cukup longgar untuk memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik terbagi ke dalam dua koalisi besar yang menamakan diri dengan koalisi kebangsaan dan koalisi kerakyatan, yang ujung-ujungnya terlibat dalam pertarungan perebutan kursi pimpinan Dewan maupun kursi pimpinan alat kelengkapan DPR yang lain (Noor, 2016).
Peran oposisi pada era pemerintahan SBY (2004–2014), meski dalam bentuk berbeda, secara substansi memperlihatkan gelagat munculnya pola “politik kartel”, yakni ketika oposisi tidak banyak bermakna dan kelompok-kelompok yang berpotensi memainkan peran oposisi justru terserap dalam pemerintahan. Meski sebagian kalangan tidak melihat hal itu sebagai murni sebuah pemerintahan kartel, kenyataan ini menunjukkan bahwa oposisi tidak berjalan efektif dan potensinya cenderung terserap dalam pemerintahan, dan hal ini tidak terelakkan. Partai-partai cenderung berkerumun mendekat kepada SBY dan membangun sebuah pemerintahan yang jauh dari semangat checks and balances (Ambardi 2009; Mietzner 2013 dalam Noor 2016). Namun demikian, pada masa ini istilah oposisi sempat muncul ketika Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memutuskan kebijakan untuk menjadikan partainya sebagai partai oposisi, setelah kalah dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2004.
Pada waktu itu Megawati dan PDI-tidak bersedia untuk bergabung dengan kabinet pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dalam perjalanannya sebagai partai oposisi, PDIP mampu menjalankan perannya secara aktif dengan cara melakukan kritik dan kontrol politik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap bertentangan dengan visi politik atau ideologi kerakyatan yang dijadikan justifikasi beroposisinya PDIP. Dengan cara demikian, berbagai kebijakan pemerintah tidak begitu saja dapat diimplementasikan tanpa terlebih dahulu memperoleh kritik dari partai oposisi.
Partai oposisi dapat memengaruhi partai-partai politik di DPR, baik yang tergabung dalam koalisi pemerintah maupun yang netral, untuk mendukung penggunaan hak-hak yang melekat pada lembaga tersebut, seperti hak angket maupun hak interpelasi. Imbas positifnya adalah “relasi eksekutif-legislatif” di Indonesia, sejak digulirkannya demokratisasi dan penerapan sistem multipartai sejak 2004 nampak lebih dinamis. Dalam beberapa hal, memang terjadi konflik tetapi sejauh ini tidak ditemukan adanya kebuntuan (Haris 2009, 122-123; Djayadi Hanan 2014, 33; sebagaimana dikutip Admojo, 2016).
Efriza (2019) mencatat bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo awal terpilih berencana untuk membentuk koalisi ramping dan koalisi tanpa syarat. Namun, pemerintahan Jokowi malah terjebak pada realitas dibutuhkannya banyak partai sebagai pendukung pemerintahannya. Awalnya, pendukung pemerintahan Presiden Jokowi berdasarkan dukungan partai politik di DPR diusung oleh PDIP dengan 129 kursi, PKB dengan 47 kursi, Partai Nasdem dengan 35 kursi, dan Partai Hanura dengan 16 kursi; dengan total jumlah dukungan anggota parlemen sebanyak 207 anggota atau total suara di parlemen sebesar 36,96 persen.
Namun, upaya memperluas jumlah partai pendukung sebagai pendukung pemerintah terus dilakukan sejak 2014 hingga 2016 yakni dengan bergabungnya PPP yang memperoleh 39 kursi, kemudian bergabungnya PAN sebesar 49 kursi, dan terakhir, bergabungnya Partai Golkar sebanyak 91 kursi. Sehingga kekuatan pendukung pemerintah akhirnya menjadi mayoritas di parlemen dengan dukungan 7 partai, atau sebanyak 386 anggota (kursi), atau total suara di parlemen sebesar 68,92 persen.
Pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak, yaitu Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan Pileg yang terdiri dari Anggota DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota. Keserentakan dua jenis pemilu ini berdampak terhadap terbentuknya dukungan partai politik yang sudah terjadi sejak awal mengusung calon Presiden Pilpres 2019. Pilpres 2019 adalah pengulangan pilpres 2014, di mana calon presiden yang berkontestasi adalah calon yang sama yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pada pilpres 2019 pasangan calon Joko Widodo dan KH. Ma’aruf Amin diusung oleh mayoritas parpol yang duduk di DPR, yaitu sebanyak 6 parpol terdiri dari PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, ditambah tiga parpol baru yaitu PSI, Perindo, dan PKPI. Sedangkan pasangan calon Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno didukung empat parpol yang duduk di DPR yaitu Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat, ditambah dua parpol baru yaitu Partai Berkarya, dan Partai Garuda.
Meskipun kontestasi Pilpres 2019 merupakan pengulangan kontestasi Pilpres 2014, friksi politik pada pilpres 2019 ini lebih tajam dan keras dibandingkan dengan pilpres 2014. Friksi ini diyakini merupakan efek dari polarisasi yang tercipta sejak pilpres 2014 dan berlanjut pada pilkada DKI 2017. Polarisasi yang terjadi dapat terlihat dari maraknya penggunaan kampanye hitam yang menyerang masing-masing kandidat. Kampanye tidak lagi berada dalam koridor normatif yang seharusnya, melainkan berkembang menjadi kampanye yang menggunakan ujaran kebencian dan berita bohong atau hoax (Sirait, 2019).
Pada tanggal 27 Juni 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan untuk menolak seluruh gugatan sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Berdasarkan putusan tersebut, pasangan capres dan cawapres Joko Widodo – Ma’ruf Amin akan memimpin Indonesia periode 2019-2024. Pada masa mempersiapkan program kinerja bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, termasuk mengenai susunan kabinet, wacana rekonsiliasi menguat (Umagapi, 2019).
Menurut Mahfud MD (sebagaimana dikutip Umagapi, 2019) kontestasi politik di Indonesia akan selalu berujung pada rekonsiliasi. Menurutnya, dalam budaya politik Indonesia rekonsiliasi selalu terjadi dan tidak dapat dihindari. Hal ini dilakukan demi kepentingan bersama, tidak mungkin antarparpol terus saling bermusuhan. Oleh sebab itu, agar pemerintahan periode mendatang dapat berkinerja optimal perlu terjadi rekonsiliasi antara kubu pasangan calon Jokowi dan kubu pasangan calon Prabowo.
Umagapi (2019) mengatakan bahwa rekonsiliasi tidak dapat hanya diartikan menjadi keturutsertaan pihak oposisi atau lawan politik di dalam kabinet pemerintahan. Sebaliknya, rekonsiliasi dimaksudkan agar setiap pihak bersedia untuk menyamakan visi dan misi mereka demi tercapai tujuan yang sama. Oleh sebab itu, meskipun rekonsiliasi dilakukan namun pihak oposisi juga harus tetap menjadi pihak yang mengawal jalannya pemerintahan. Hal ini penting agar pemerintahan yang berjalan tidak berkuasa secara mutlak dan mengarah ke otoriter. Dalam pemerintahan, posisi oposisi tidak berarti harus menentang seluruh kebijakan pemerintah, namun dapat menawarkan solusi atas sebuah permasalahan yang dihadapi bangsa.
Bergabungnya Prabowo dan Sandiaga Uno, secara otomatis menjadikan peta kekuatan politik di parlemen dan secara nasional berubah. Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin untuk masa jabatan 2019-2024 secara matematis telah memiliki surplus dukungan, atau bisa disebut telah memiliki kekuatan mayoritas dalam peta politik Indonesia. Beberapa kalangan menilai ‘koalisi gemuk’ yang dibentuk Presiden Joko Widodo dipandang menjadi ‘sinyal negatif’ bagi demokrasi. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hurriyah (dalam BBC Indonesia, 23 Oktober 2019) memandang dalam periode kedua pemerintahannya, Jokowi berfokus pada mengamankan dukungan elite politik sehingga menjadi pilihan strategis untuk merangkul sebanyak-banyaknya elite.
Namun, ini menjadi sinyal yang sebenarnya negatif untuk perkembangan demokrasi ke depannya. Masalah di dalam mengelola “koalisi gemuk” adalah sulitnya menggabungkan semua partai politik dalam gerbong yang sama. Masing-masing partai dalam gerbong punya konflik sendiri dengan partai lain dan punya kepentingan yang berbeda, boleh jadi dalam banyak hal sikap politik mereka berbeda.
Pengamat politik LIPI, R. Siti Zuhro (2019) menyebutkan bahwa sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Kampanye lebih merupakan pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan menjawab persoalan bangsa. Parpol hanya memperdebatkan soal electoral threshold sebagai legitimasi kelayakan, namun minim wacana mengenai ide atau program yang hendak ditawarkan pada rakyat. Perhatian parpol pada rakyat umumnya hanya terjadi pada saat pemilu ketika mereka membutuhkan dukungan suara.
Setelah itu, hak dan kedaulatan rakyat tercampakkan. Zuhro menyebutkan bahwa Parpol tampak sibuk dan terjebak dalam pergulatan kepentingannya sendiri dan mengabaikan massa yang menjadi pendukungnya dalam pemilu. Proses pengabaian ini secara lambat tapi pasti telah mendelegitimasi eksistensi parpol. Bagi massa, parpol gagal melaksanakan peran dan fungsinya dan cenderung menggunakan institusinya hanya untuk memperjuangkan kekuasaan dan kepentingannya sendiri.
Arbi Sanit (2015) menyebutkan bahwa selama merdeka, secara berurutan lndonesia telah berusaha melembagakan sembilan varian Sistem Politik Indonesia (SPI). SPI ini dikenali dari pengaturan tatanan dan alur proses kekuasaan bernegara, di dalam konstitusi dan peraturan perundangan jabarannya. Secara informal SPI tergambar dari jaringan kelompok dan Ormas serta Organisasi Politik, yang berpengaruh kepada dan atau dipengaruhi oleh tatanan dan proses formal tersebut. Durasi keseimbangan dan keteraturan saling kontrol dan pengaruh dimaksudkan, menggambarkan daya tahan stabilitas dan efektivitas sistem politik.
SPI sebagaimana disebutkan Sanit (2015) terdiri dari empat varian, yaitu Demokrasi Parlementerianisme, Demokrasi Semi Presidensialisme, Demokrasi Presidensialisme minimalis, dan Semi Presidensialisme Demokratis. Varian Demokrasi Parlementerianisme berlangsung pada masa fungsionalisasi KNIP, Federalisme, berdasar UUD Sementara, dan hasil Pemilu 1955. Kemudian, varian Demokrasi Semi Presidensialisme terjadi pada masa otoritarian Orla dan Orba. Varian reformatif Demokratis berlangsung saat kepemimpinan presiden Habibie. Varian Semi Presidensialisme Demokratis yaitu pada pemerintahan presiden Gus Dur dan Megawati. Kemudian, varian Demokrasi Presidensialisme minimalis, menurut konstitusi dan praktik adalah presidensialisme minimalis, yaitu di masa presiden SBY dan Jokowi.
Intensitas pergeseran Sistem Politik Indonesia dan kabinet ini, menurut Sanit (2015), menggambarkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan dalam jangka panjang. Hal ini terjadi karena di satu sisi berakar kepada kompleksitas konflik yang bersifat akut, sehingga tidak terselesaikan pada waktunya dan secara tepat. Pada sisi lain disebabkan oleh inkoherensi tatanan dan prosesnya. Benih konflik terpendam, yang rentan terpicu oleh ketegangan dalam perjuangan hak kelompok atau golongan, merebak menjadi konflik intra dan antar partai, dan memuncak menjadi konflik kelembagaan negara. Ideologisasi dan politisasi konflik menjadikannya sukar dikompromikan, hingga berlarut dan membesar, yang setelah terakumulasi dengan berbagai permasalahan masyarakat-bangsa dan negara-bangsa, akhirnya menajam ke dalam dua pilihan yaitu “melanjutkan vs mengganti” Sistem Politik Indonesia.
Karena itulah terjadi ketidakkoherenan sistem politik parlementerianisme yang tercermin dari kehadiran sistem multipartai, yang tidak didampingi dengan budaya politik Koalisi Besar Permanen (KBP). Sekalipun hal ini hadir dalam rangka menerapkan prinsip keseimbangan, kebebasan rakyat, kemajemukan, namun untuk efektivitas dan stabilitas pemerintahan, situasi ini mengecilkan kesempatan untuk membangun kekuatan mayoritas pendukung pemerintah.
Menurut Efriza (2019), kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial menyebabkan koalisi menjadi barang wajib. Sebab sistem kepartaian di Indonesia adalah sistem multipartai moderat dengan kisaran partai yang memperoleh dukungan cukup berarti berada pada kisaran empat sampai sembilan partai saja. Tetapi sayangnya tidak ada satu pun partai yang dominan. Kecenderungan ini umum terjadi di Indonesia yang terlihat dari hasil Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014 yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan hasil Pemilu 1955.
Sistem multipartai, sebagaimana namanya, merupakan sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai politik dominan. Menurut Maurice Duverger (1954, dalam Amalia, 2013), sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk. Dalam sistem ini hampir tidak ada partai yang memenangi pemilu mutlak. Oleh karena itu koalisi mutlak diperlukan untuk memperkuat pemerintahan. Namun, dukungan koalisi bisa ditarik kembali sewaktu-waktu.
Selain itu, dalam sistem ini tidak ada kejelasan posisi partai oposisi sebab sewaktu-waktu partai oposisi bisa menjadi bagian pemerintahan. Dengan kata lain, dalam sistem ini seringkali terjadi siasat yang berubah-ubah sesuai dengan kegentingan situasi yang dihadapi masing-masing partai politik. Sistem ini menggunakan sistem pemilu proporsional/perwakilan berimbang (proportional representation) yang memberi kesempatan luas bagi pertumbuhan partai-partai dan golongan-golongan baru.
Mengutip Bunte & Ufen (2009), Firman Noor menyatakan bahwa kondisi melemahnya oposisi ini tampak mirip dan menunjukkan sebuah warisan masa lalu, terutama dari era Orde Baru, yakni oposisi pada akhirnya cenderung tercerai-berai dan tampak kehilangan posisi. Kalau dulu, hal tersebut lebih dipengaruhi oleh tekanan rezim, namun pada saat ini perilaku elite partailah yang berperan dalam melemahkan kedudukan oposisi sebagai efek pilihan pragmatis mereka untuk selalu mendekat dan berada dalam lingkar kekuasaan.
Di samping itu, jika dibanding dengan demokrasi di negara-negara Barat atau kehidupan politik nasional era 1950-an, peran besar para elite atau oligarki juga menunjukkan lemahnya peran ideologi dalam kehidupan internal partai saat ini, yang kemudian berimbas pada perilaku politiknya.
Kondisi ini diperburuk oleh pemahaman dari banyak elite atau tokoh berpengaruh partai yang juga masih melihat oposisi sebagai sesuatu yang tidak relevan dengan kehidupan politik saat ini. Mereka menyatakan hal itu dengan berbagai alasan, seperti tidak sesuai dengan karakter bangsa, tidak dikenal dalam sistem presidensial, atau tidak sejalan dengan idealisme partainya. Selain itu, cukup jelas terlihat bahwa hingga kini oposisi yang terlembaga masih belum mendapat dukungan kuat dari kalangan masyarakat.
Konsep oposisi tidak terlalu mengakar atau kurang mendapat dukungan masyarakat, terutama karena pemahaman oposisi yang tidak tepat. Dengan minimnya dukungan ini, oposisi di era Reformasi tampak berada dalam posisi yang gamang dan justru terlihat terkucilkan dari opini yang berkembang di masyarakat tentang pemerintah, yang kerap dimanipulasi oleh pemerintah itu sendiri.
Dampaknya, alih-alih menjadi ranah bagi kehidupan demokrasi yang sehat, Indonesia saat ini justru terjebak dalam praktik oligarki yang masih menempatkan kepentingan sedikit orang di atas kepentingan rakyat banyak. Menurut Firman Noor (2020), kondisi demokrasi Indonesia saat ini berada pada kecenderungan post-democracy. Fenomena ini sebenarnya telah memiliki gejala-gejala sejak awal reformasi.
Secara spesifik setidaknya ada beberapa karakteristik demokrasi di Indonesia saat ini yang mencerminkan demokrasi tanpa demos. Pertama, lemahnya pelaksanaan checks and balances yang terlihat dari lemahnya peran partai, DPR, di hadapan eksekutif. Kedua, meredupnya sikap kritis civil society sebagai mitra pemerintah yang mengakibatkan demokrasi menjadi tumbuh dalam “tanah yang gersang”. Ketiga, kepemimpinan nasional tidak membawa pencerahan/pendewasaan berpolitik.
Para elite tidak cukup berhasil dalam memelihara soliditas masyarakat, menghindari personifikasi politik, dan mendorong demokrasi substansial-rasional. Keempat, lemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, baik pada level elite ataupun masyarakat, seiring dengan meningkatnya oportunisme di kalangan elite dan meredupnya pendidikan politik serta melemahnya ekonomi masyarakat. Kelima, memudarnya partisipasi rakyat yang otonom dan genuine yang ditandai dengan maraknya politik uang dan manipulasi informasi. Keenam, terjadinya “de-demokratisasi internal” pada lembaga-lembaga politik, terutama partai yang justru menyuburkan nilai-nilai anti-demokrasi dan meningkatkan personifikasi lembaga demokrasi. Ketujuh, terjadinya diskriminasi politik atas nama SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dan rasa kedaerahan. (*)
Daftar Pustaka:
Dahl, A. Robert. 1982. Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol. Sahat Simamora (ed). Jakarta: Rajawali. Hlm. 9-10
Effendi, Edy A. (ed). 1998. Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer. Jakarta: Paramadina.
Madjid, Nurcholish. 1999. Cita-cita Politik Islam Era Reformasi. Jakarta: Paramadina
Marijan, Kacung. 2010. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Cetakan ke-6 (2007). Jakarta: Grasindo.
Jurnal dan Artikel
Admojo, Tuswoyo. Februari 2016. Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014. Jurnal Politik, Vol. 1 (2). Materi tersedia di
http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/18, diakses 16 Januari 2021
Amalia, Luky Sandra. Desember 2013. Evaluasi Sistem Kepartaian di Era Reformasi. Jurnal Penelitian Politik, Volume 10 (2). Materi tersedia di
http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/440/253, diakses 16 Januari 2021.
Efriza. Juni 2019. Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemilu Serentak 2019. Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16 (1): 1-15. Materi tersedia di
http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/772. Diakses 15 Januari 2021
Munadi. Juni 2019. Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia, Jurnal Resolusi Vol. 2 (1). Materi tersedia di https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/726, diakses 16 Januari 2021.
Noor, Firman. Juni 2016. Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1). Materi tersedia di
http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/358. Diakses 8 Januari 2021.
______. 2020. Demokrasi Indonesia dan Arah Perkembangannya di Masa Pandemi COVID-19. Artikel pada Kolom Pusat Penelitian Politik LIPI. 12 MEI 2020. Materi diakses pada 16 Januari 2021 di http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1394-demokrasi-indonesia-dan-arah-perkembangannya-di-masa-pandemi-covid-19
Sanit, Arbi. Agustus 2015. Pematangan Demokrasi dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan dan Kepemimpinan. Jurnal Politik, Vol. 1 (1). Materi tersedia di http://jurnalpolitik.ui.ac.id/index.php/jp/article/view/12, diakses 16 Januar 2021.
Sirait, Ferdinand Eskol Tiar. Desember 2019. Ujaran Kebencian, Hoax dan Perilaku Memilih (Studi Kasus Pada Pilpres 2019 di Indonesia). Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16 (2): 179-190. Materi tersedia di
http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/806, diakses 16 Januari 2021.
Suryani. 2016. Neo Modernisme Islam Indonesia: Wacana Keislaman dan Kebangsaan Nurcholish Madjid. Jurnal Wacana Politik, Vol. 1 (1): Hal 29-40. Materi tersedia di http://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/10548. Diakses 16 Januari 2021.
Umagapi, Juniar Laraswanda, Debora Sanur L. Juli 2019. Rekonsiliasi Politik dan Pembentukan Kabinet Baru Periode 2019-2024. Info Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Vol. XI (13). Materi tersedia di https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-13-I-P3DI-Juli-2019-2044.pdf, diakses 16 Januari 2021
Wijayanti, Ari. 2002. Dinamika Oposisi Pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Skripsi. Fisip Universitas Jember. Materi tersedia di
https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/81766, diakses 15 Januari 2021.
Zuhro, R. Siti. Juni 2019. Demokrasi Dn Pemilu Presiden 2019 (Democracy And The 2019 Election). Jurnal Penelitian Politik, Vol. 16 (1): 69–81. Materi tersedia di http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/782, diakses 8 Januari 2021.
Internet
BBC Indonesia. Kabinet Jokowi: ‘Koalisi gemuk’ setelah Prabowo Subianto merapat ke pemerintah, sinyal negatif demokrasi Indonesia? Diakses 24 Desember 2020, materi tersedia di https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50120592
Oposisi. https://id.wikipedia.org/wiki/Oposisi_(politik) diakses tanggal 24 Desember 2020.