Oleh: Radhar Tribaskoro
ROCKY Gerung, filsuf publik yang dikenal dengan argumentasi tajamnya, baru-baru ini melontarkan kritik keras terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM). Menurut Rocky, KDM adalah pemimpin yang lebih menonjolkan visualisasi dibandingkan visi; lebih sibuk tampil daripada berpikir. Ia bahkan menyebut KDM sebagai “fotokopi Mulyono”, sindiran kepada Jokowi, karena dianggap sama-sama mengandalkan gaya ketimbang gagasan. Rocky menyimpulkan bahwa pendukung KDM tidak berbeda dari pendukung Jokowi: buzzer yang siap membela idolanya tanpa berpikir.
Kritik Rocky ini patut dihargai sebagai bagian dari diskursus publik. Namun, ada baiknya kita mendudukkannya secara proporsional. Apakah benar pemimpin yang menonjol secara visual berarti dangkal secara intelektual? Apakah benar publik yang menyukai kerja nyata selalu anti terhadap visi dan konsep? Dan yang paling penting: apakah pemimpin yang tidak mengartikulasikan gagasan secara teoretis berarti tak punya fondasi berpikir?
Antara Visual dan Visi
Visual dan visi bukanlah dua hal yang bertentangan. Dalam dunia politik modern yang mediatized (Castells, 2009), visual adalah bagian dari strategi komunikasi. Visualisasi tindakan—seperti KDM yang membongkar pasar, membersihkan sungai, atau mendampingi warga—tidak otomatis berarti ketiadaan visi. Justru visual menjadi alat untuk menunjukkan proses kerja, transparansi kebijakan, dan mengajak publik untuk terlibat.
Rocky benar bahwa visi penting. Namun visi tanpa keberanian bertindak hanyalah retorika. Sebaliknya, tindakan tanpa narasi hanya menjadi tontonan. KDM mencoba menggabungkan keduanya: ia tidak berteori di atas podium, tetapi membangun narasi lewat tindakan. Ini adalah bentuk dari pragmatic visioning—visi yang ditunjukkan lewat praktik, bukan hanya pidato.
Sejarah politik Indonesia penuh dengan tokoh besar yang tidak dikenal karena konsepnya, tetapi karena integritas dan keberaniannya. Jenderal Sudirman, misalnya, tidak meninggalkan satu pun teori politik, tetapi pilihannya untuk bergerilya saat Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda adalah keputusan strategis yang mengandung visi kebangsaan: bahwa kemerdekaan tidak boleh dinegosiasikan.
Di dunia internasional, kita bisa menyebut:
– Nelson Mandela: meskipun memiliki pemahaman ideologis, ia tidak dikenal sebagai teoritikus, tetapi sebagai simbol rekonsiliasi dan kemanusiaan.
– Vaclav Havel: lebih dikenal sebagai sastrawan dan praktisi moral daripada pemikir politik, namun ia mampu memimpin Cekoslowakia keluar dari komunisme.
– Angela Merkel: tidak memproduksi teori besar, tetapi diakui sebagai pemimpin visioner karena konsistensi moral dan kebijakan berbasis bukti.
– Mother Teresa: bukan pemikir ideologis, tetapi dedikasinya menjadi wajah nyata dari nilai-nilai kemanusiaan.
– Dalam pengalaman saya pribadi banyak teman yang tidak pandai menjelaskan hal-hal sederhana seperti demokrasi atau otokrasi, tetapi ketika zaman memanggilnya melawan rejim Orde Baru yang berada disaf terdepan. Ia tidak fasih mengkonseptualisaikan pikirannya tetapi ia bersedia membayar dengan tahun-tahun penjara dimana masa depan bangsa yang lebih baik.
Mereka tidak menulis teori politik, tetapi praktiknya mengubah arah sejarah.
Visi Tak Harus Verbalis
Tidak semua pemimpin berpikir dalam kerangka konseptual formal. Ada yang berpikir dalam bentuk nilai, prinsip, dan intuisi moral. Dedi Mulyadi, misalnya, menunjukkan konsistensi berpihak kepada rakyat kecil, keberanian mengintervensi pasar kekuasaan (seperti dalam kasus dana hibah pesantren), serta keteguhan melawan rapat-rapat tak berujung yang hanya mempertahankan status quo. Ini bukan populisme kosong, tetapi moral disruption.
Tentu, Dedi bukan pemikir akademis. Tapi ini tidak otomatis membuatnya anti-intelektual. Ia membaca realitas secara kontekstual, bukan tekstual. Ia membaca keluhan warga, bukan jurnal internasional. Ia menggunakan media sosial sebagai ruang deliberasi, bukan sekadar panggung pencitraan.
Di sini saya tidak ingin mengatakan bahwa sahabat saya Rocky Gerung tidak menyukai orang-orng biasa. Ia menyukai pikiran yang bernas, argumentasi yang jernih, dan keberanian berpikir. Kalau ia tampak hanya akrab dengan para intelektual, itu lebih karena ia membutuhkan ruang berpikir yang resonan, bukan karena menolak atau menilai rendah orang-orang “biasa.”
Apa yang disampaikan Rocky bisa dibaca sebagai ekspresi dari habitus intelektual yang menghargai argumentasi konseptual. Dalam kacamata Bourdieu, Rocky sedang menggunakan modal budayanya untuk mempertahankan medan dominasi simbolik: bahwa intelektual yang baik adalah yang berpikir abstrak.
Namun pemimpin seperti KDM bermain di medan berbeda: bukan kampus atau seminar, tetapi pasar, kampung, dan jalanan. Ia bukan pemilik modal simbolik akademik, tapi punya legitimasi moral dan tindakan. KDM tidak mengartikulasikan konsep seperti deliberatif, distribusi, atau governance. Tapi ia menjalankannya.
Audiens KDM dan Buzzerisme
Rocky menuduh pendukung KDM mirip dengan buzzer Jokowi: membabi buta dan anti-kritik. Ini tuduhan serius, dan perlu dilihat secara lebih teliti. Faktanya, banyak pendukung KDM adalah warga yang merasa diperhatikan. Mereka bukan buzzer profesional, tetapi warga digital yang melihat langsung dampak kerja KDM di medsos.
Ada perbedaan antara fanatisme buta dan solidaritas digital. Publik yang membela KDM bukan karena ia suci, tetapi karena ia hadir. Ia hadir dalam banjir, di pasar, di kampung, bukan hanya di baliho.
Rocky Gerung memberikan kontribusi penting bagi demokrasi: ia memaksa kita berpikir. Tapi berpikir saja tidak cukup. Demokrasi butuh kerja nyata. Dedi Mulyadi mungkin tidak menyampaikan konsep seperti deliberasi, inklusi, atau redistribusi. Tapi ia melakukannya dalam bentuk kebijakan. Ia tidak banyak berkata, tetapi ia bekerja.
Dalam dunia yang penuh noise politik, pemimpin yang hadir dan bekerja nyata adalah bentuk artikulasi visi tersendiri. Visi bukan hanya apa yang diucapkan, tetapi apa yang diperjuangkan dan diwujudkan. Visual bukan sekadar pencitraan, tetapi bisa menjadi kanal akuntabilitas dan pembelajaran.
Mungkin, di zaman ketika politik terlalu penuh basa-basi, kita justru butuh lebih banyak pemimpin yang diam-diam berpikir, tapi berani bertindak.@
Referensi:
Castells, M. (2009). Communication Power. Oxford University Press.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Harvard University Press.
Heifetz, R. A. (1994). Leadership Without Easy Answers. Harvard University Press.
Luhmann, N. (1995). Social Systems. Stanford University Press
*) Penulis pernah menjadi Sekertaris DPD Gerindra Jawa Barat





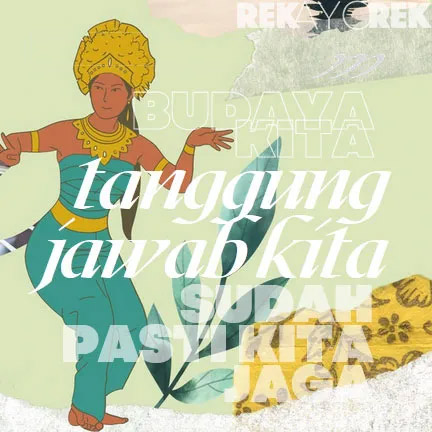






Discussion about this post