Oleh: Sugiyanto (SGY)-Emik
BEBERAPA hari lalu, seorang teman wartawan bertanya kepada saya mengenai penolakan terhadap program Normalisasi Sungai Ciliwung. Karena kesibukan, baru hari ini saya sempat menuliskannya dalam artikel ini.
Sebenarnya, minggu ini saya berencana menyelesaikan artikel berjudul “Minggu Depan Bahas Tuntas Pembatalan ITF Sunter dan Pembangunan RDF Rorotan Plant.” Namun, mengingat sejumlah isu mendesak yang menyangkut kepentingan masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta, saya putuskan menunda sementara penyelesaian artikel tersebut.
Kemarin, Senin 15 April 2025, saya juga menulis artikel berjudul “Kritik Dewan Francine dan LSM Bagus: Penyesuaian Tarif Air untuk Mencapai Cakupan Pelayanan 100 Persen Air Bersih Adalah Langkah yang Penting.” Artikel tersebut menanggapi kritik terhadap kebijakan penyesuaian tarif air minum PAM Jaya di Jakarta sebagaimana diatur dalam Pergub No. 37 Tahun 2024. Kritik datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta, Francine Widjojo, serta kalangan masyarakat sipil yang menilai kebijakan ini bermasalah secara hukum dan tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
Namun, saya berpandangan bahwa kebijakan tersebut sangat penting dan strategis demi mencapai target cakupan layanan air bersih 100 persen pada tahun 2030, sejalan dengan komitmen global dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Kali ini, saya akan membahas penolakan terhadap normalisasi Sungai Ciliwung. Setelah ini, saya akan menulis artikel mengenai dugaan penggunaan media sosial untuk pencitraan oleh kepala daerah, proyek ITF-RDF, dan isu-isu penting lainnya.
Gagasan normalisasi Sungai Ciliwung mengemuka setelah banjir besar melanda Jakarta pada tahun 2012. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menilai perlunya peningkatan kapasitas angkut sungai agar air tidak meluap. Gagasan tersebut kemudian mulai direalisasikan pada masa Gubernur Joko Widodo (Jokowi) dan dilanjutkan oleh wakilnya yang kemudian menjadi gubernur, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Hingga era Ahok, proyek normalisasi telah berjalan sepanjang 16 kilometer. Namun, ketika Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur pada akhir 2017, proyek ini terhenti. Selain karena kendala pembebasan lahan, muncul pula penolakan dari sebagian masyarakat yang terdampak relokasi. Anies mengganti pendekatan normalisasi dengan program seperti Gerebek Lumpur dan naturalisasi sungai. Ia menilai normalisasi tidak efektif, sebab beberapa wilayah yang telah dinormalisasi masih tetap dilanda banjir.
Politisi PDIP Ida Mahmudah mengaku heran mengapa pada masa kepemimpinan Jokowi dan Ahok, proses pembebasan lahan dapat berjalan relatif lancar, sementara pada masa Anies tidak kunjung dilakukan. Akibatnya, proyek normalisasi atau naturalisasi mandek. Padahal, anggaran pembebasan lahan sebesar Rp 1 triliun sudah dialokasikan dalam APBD 2021, namun akhirnya harus dikembalikan karena proyek tidak terlaksana.
Ketua DPRD DKI Jakarta saat itu, Prasetyo Edi Marsudi, juga menyoroti hal yang sama. Ia menyebut Anies tidak berani menjalankan program yang disebutnya sebagai naturalisasi karena khawatir dicap sebagai “tukang gusur.” Menurut politisi yang akrab disapa Pras ini, Anies seharusnya tetap melaksanakan program tersebut karena telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) yang disepakati bersama oleh DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.
Merumuskan Solusi Bijak atas Penolakan Normalisasi
Terkait persoalan penolakan terhadap normalisasi Sungai Ciliwung, diperlukan langkah yang tegas dari Pemprov DKI Jakarta. Keberanian dan ketegasan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sangat dibutuhkan. Relokasi atau penggusuran memang menjadi pilihan yang sulit dihindari. Untuk membawa perubahan besar di Jakarta, kadang dibutuhkan kebijakan yang tidak populer. Namun, apabila kebijakan itu bertujuan untuk kebaikan bersama, maka harus dijalankan dengan keberanian dan komitmen yang kuat.
Normalisasi Sungai Ciliwung adalah program strategis dalam mengatasi banjir yang kerap terjadi di Jakarta, terutama di wilayah padat penduduk seperti Kampung Melayu dan Bukit Duri. Meski telah direncanakan sejak lama, realisasi program ini menghadapi banyak hambatan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah penolakan dari warga yang tinggal di bantaran sungai.
Bagi warga, rumah di bantaran Ciliwung bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber penghidupan, ruang sosial, dan warisan keluarga yang dibangun bertahun-tahun lamanya. Ikatan emosional yang kuat terhadap lingkungan tersebut membuat rencana relokasi menjadi hal yang sangat berat. Ketika pemerintah hadir dengan proyek normalisasi yang berdampak pada penggusuran, tanpa disertai pendekatan sosial dan kemanusiaan yang memadai, maka penolakan pun muncul secara alami.
Selain ikatan emosional, ada pula persoalan keadilan dan kepastian hukum. Banyak warga merasa bahwa relokasi tidak menjamin kehidupan yang lebih baik. Rumah susun sebagai hunian pengganti seringkali dipersepsikan menurunkan kualitas hidup, karena ruang terbatas, akses ekonomi yang terbatas, dan fasilitas sosial yang tidak memadai. Kurangnya komunikasi yang transparan dan partisipatif dari pemerintah turut memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap proyek ini.
Saat ini, dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru 17,17 kilometer yang telah dibangun tanggul. Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum dibebaskan lahannya. Proses ini diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah serta Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 yang telah diubah melalui PP No. 39 Tahun 2023.
Berdasarkan regulasi tersebut, pembebasan tanah dilakukan melalui empat tahap: perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Pemprov DKI diperkirakan masih harus membebaskan lahan seluas 12–13 hektare, mencakup sekitar 634 bidang tanah. Wilayah Cawang menjadi lokasi dengan jumlah bidang terbanyak, yakni 411 bidang dengan luas mencapai sekitar 58.946 meter persegi.
Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan pemerintah harus berubah. Normalisasi sungai tak cukup hanya dipahami sebagai proyek teknis pengendalian banjir, tetapi perlu dilihat sebagai bagian dari pembangunan sosial yang manusiawi dan berkeadilan. Pemerintah harus memastikan bahwa hunian pengganti layak secara kualitas, terhubung dengan pusat ekonomi warga, dan tidak memutus akses terhadap penghidupan mereka.
Solusi bijak lainnya adalah melibatkan tokoh masyarakat, organisasi sipil, dan kalangan akademisi secara aktif dalam proses perencanaan, sosialisasi, hingga pelaksanaan program. Keterlibatan yang inklusif dan transparan akan menumbuhkan rasa memiliki dari warga serta meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
Dengan pendekatan yang bijak, partisipatif, dan berkeadilan, impian menjadikan Sungai Ciliwung sebagai sungai yang tertata, aman, dan tidak lagi menjadi sumber banjir bisa terwujud. Normalisasi yang memanusiakan, bukan menggusur, adalah solusi yang tepat untuk masa depan Jakarta yang lebih tangguh dan manusiawi.
Namun demikian, jika relokasi atau penggusuran menjadi langkah yang tidak bisa dielakkan, maka harus dijalankan secara adil dan manusiawi. Untuk membawa Jakarta menuju perubahan besar, memang terkadang diperlukan keputusan yang kurang populer. Tapi jika kebijakan tersebut dilandasi semangat untuk kebaikan bersama, maka perubahan itu layak untuk diperjuangkan dengan penuh keberanian dan komitmen.@
*) Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrat)





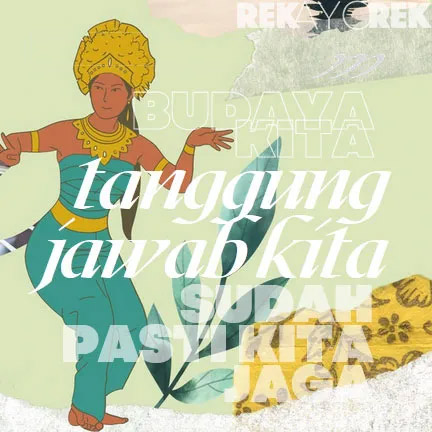






Discussion about this post