Oleh: Radhar Tribaskoro
DALAM tulisan berjudul “Kritik terhadap Reformasi. Mari Kembali ke Sistem Pilpres di MPR RI”, Prof. Daniel Mohammad Rosyid mengajukan argumen radikal: bahwa kegagalan demokrasi Indonesia hari ini terutama bersumber dari reformasi konstitusional tahun 2002, khususnya adopsi sistem pemilihan presiden secara langsung. Bagi beliau, lahirnya Jokowi, dua kali terpilih sebagai presiden, adalah bukti utama kegagalan sistem ini.
Tulisan tersebut menolak demokrasi liberal dan mengusulkan kembali ke sistem awal UUD 1945, di mana presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kritik seperti ini semakin sering kita jumpai dalam satu dekade terakhir, seiring kemerosotan kualitas demokrasi Indonesia. Namun, pertanyaannya bukan apakah demokrasi kita sedang mengalami regresi — itu sudah cukup jelas — melainkan apakah akar persoalannya benar terletak pada pemilihan langsung?
Tulisan ini bertujuan membedah argumen Prof. Rosyid dengan cermat dan menunjukkan bahwa menyalahkan mekanisme pemilihan langsung atas seluruh kerusakan demokrasi justru adalah penyederhanaan berbahaya. Kita akan menjawab beberapa poin penting satu per satu, dengan pendekatan ilmiah.
1. Apakah Demokrasi Gagal Hanya Karena Jokowi Terpilih Dua Kali?
Prof. Rosyid menyebut Jokowisme sebagai “anak kandung UUD 2002”, dan menganggap keberhasilan Jokowi dalam dua pemilu sebagai bukti kegagalan sistem. Ini adalah bentuk post hoc fallacy: menganggap bahwa karena peristiwa A terjadi sebelum peristiwa B, maka A menjadi penyebab B.
Terpilihnya Jokowi bukan bukti sistem gagal. Justru, ia menunjukkan bahwa sistem memberikan ruang mobilitas politik dari luar elite tradisional. Jokowi adalah figur pertama sejak Reformasi yang bukan ketua partai, bukan jenderal, bukan tokoh ormas besar — dan justru karena itulah ia terpilih.
Pertanyaannya bukan mengapa Jokowi bisa menang, tapi bagaimana ia menjalankan kekuasaan setelahnya. Kritik terhadap Jokowi tidak otomatis berarti pemilihan langsung gagal; bisa jadi yang gagal adalah sistem check and balance, partai politik, atau penegakan hukum.
2. Kalau Pilpres Langsung Gagal, Apakah Kepala Daerah dan DPR Juga Tak Layak Dipilih Langsung?
Jika kita menerima logika bahwa pemilihan langsung melahirkan “bandit politik”, mengapa hanya pemilihan presiden yang disasar? Bukankah DPR, DPD, DPRD, bupati, wali kota, dan gubernur juga dipilih langsung?
Mengapa tidak sekalian menghapus semua pemilu dan kembali ke sistem perwakilan utuh atau bahkan penunjukan?
Jawaban terhadap pertanyaan ini menunjukkan bahwa kritik terhadap sistem pemilihan langsung kerap dilandasi nostalgia terhadap otoritarianisme “tertib” alih-alih evaluasi komprehensif atas disfungsi kelembagaan.
3. Apakah Memilih Lewat MPR Lebih Rasional, Murah, dan Akuntabel?
Argumen bahwa MPR lebih “bijaksana, murah, dan akuntabel” adalah klaim yang perlu diuji. Dalam sejarah Indonesia, pemilihan presiden oleh MPR tidak terbukti menghindari manipulasi atau kooptasi elite.
Pemilihan Soeharto oleh MPR selama 32 tahun adalah contoh ekstrem dari kooptasi politik. Bahkan setelah Reformasi, pemilihan Gus Dur dan Megawati oleh MPR juga penuh kompromi politik di belakang layar.
Sebaliknya, pemilu langsung memberi rakyat hak dan kesempatan untuk ikut menentukan, meskipun belum ideal. Masalahnya bukan pada akses rakyat memilih, melainkan pada kualitas informasi, integritas penyelenggara, dan kontrol atas modal politik.
4. Apakah Pilpres Langsung Selalu Memicu Sengketa di Mahkamah Konstitusi?
Prof. Rosyid menyatakan bahwa pemilu selalu disengketakan di MK. Benar bahwa sejak 2004 semua pilpres berakhir di MK, tapi apakah itu bukti kegagalan sistem?
Dalam banyak negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat, pemilu bisa disengketakan. Proses hukum adalah mekanisme koreksi, bukan bukti kegagalan sistem. Justru keberadaan MK sebagai jalur konstitusional untuk menyelesaikan konflik adalah kekuatan demokrasi — bukan kelemahannya.
5. Apakah Efek Olson (asal pilih massal) Merusak Demokrasi?
Prof. Rosyid menggunakan teori mass random voting dari Mancur Olson untuk menyebut bahwa pemilih cenderung memilih secara irasional. Teori ini relevan, namun harus ditinjau dalam konteks. Benar bahwa dalam pemilu dengan skala besar, pemilih bisa tidak rasional.
Namun solusinya bukan menghapus hak pilih rakyat, melainkan meningkatkan literasi politik, memperbaiki pendidikan kewarganegaraan, memperbaiki desain surat suara, dan memperkuat lembaga penyiaran publik. Jangan menyalahkan rakyat karena tidak “mampu memilih”; tugas sistemlah untuk membuat pilihan itu rasional dan transparan.
6. Apakah Kembalinya GBHN dan Mandataris MPR akan Mencegah Bandit Politik?
Prof. Rosyid mengusulkan agar presiden kembali menjadi mandataris MPR dengan tugas menjalankan GBHN. Namun sejarah menunjukkan bahwa GBHN bukanlah jaminan tata kelola yang demokratis. Di bawah Orde Baru, GBHN justru menjadi legitimasi bagi pembangunan otoriter.
Lagipula, di negara demokrasi modern, presiden bukan sekadar eksekutor rencana MPR. Ia adalah pemimpin politik yang harus mempertanggungjawabkan programnya langsung kepada rakyat. Jika presiden hanya “petugas” MPR, maka elite-lah yang akan mendefinisikan arah negara — bukan rakyat.
7. Menyalahkan UUD 2002: Sebuah Generalisasi yang Gagal Menjawab Kompleksitas
Kritik terhadap amandemen UUD 1945 memang valid dan harus terus dilakukan. Namun menyalahkan keseluruhan sistem hanya karena satu figur (Jokowi) atau satu hasil pemilu adalah generalisasi yang gagal memahami kompleksitas sistem politik.
Fakta bahwa sistem demokrasi bisa melahirkan elite yang buruk bukan berarti sistem itu rusak, tapi bahwa pengaman institusional dan kultural kita belum cukup kuat. Penyalahgunaan kekuasaan bisa terjadi dalam sistem apapun — otoriter maupun demokratis. Bedanya, dalam demokrasi, kita punya ruang koreksi.
8. Siapa yang Memanipulasi Sistem, Siapa yang Dikambinghitamkan?
Masalah terbesar dalam demokrasi Indonesia hari ini bukan terletak pada rakyat, tetapi pada elite politik yang menggunakan segala celah sistem untuk memperkuat dominasi, termasuk politik uang, pencitraan, dan kooptasi lembaga negara.
Mengembalikan pemilihan ke MPR justru bisa memperparah kooptasi tersebut. Dengan jumlah anggota MPR yang terbatas dan berasal dari partai politik, biaya politik untuk “membeli” suara akan lebih murah dan lebih tertutup dibanding kampanye terbuka kepada jutaan rakyat.
Kesimpulan: Demokrasi Butuh Perbaikan, Bukan Pembatalan
Kita tidak menyangkal bahwa demokrasi Indonesia sedang menghadapi krisis serius: politik uang merajalela, institusi pengawas lumpuh, dan akuntabilitas rendah. Namun solusinya bukan dengan menghapuskan demokrasi, melainkan dengan memperbaikinya secara sistemik.
Pemilihan langsung bukanlah akar masalah, tetapi bagian dari sistem yang belum bekerja sempurna. Jalan keluar dari krisis bukanlah kembali ke masa lalu, tapi melangkah maju dengan membangun demokrasi yang lebih partisipatif, transparan, dan berbasis pada meritokrasi serta etika publik.
Menolak pemilu langsung berarti mencabut hak dasar rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Dan ketika rakyat tak lagi punya hak pilih, maka yang tinggal hanyalah kekuasaan para elite — dan itulah sebenarnya bentuk kemunduran paling nyata dalam demokrasi.@





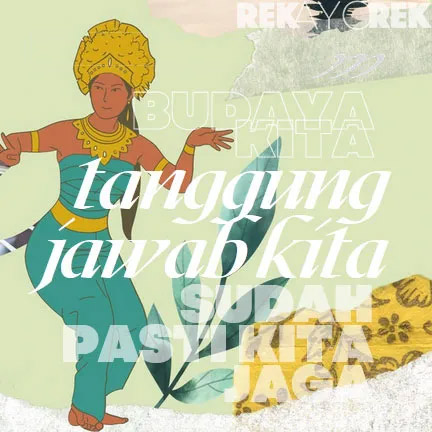






Discussion about this post