Oleh: IM. Sumarsono
Oposisi berasal dari bahasa Latin, yaitu opponere. Artinya menentang, menolak, melawan. Oposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa.
Dalam bahasa Inggris, kata oposisi adalah opposition. Ini juga berarti “berlawanan” karena kata ini lahir dan tumbuh pertama kali di dalam parlemen ketika terdapat dua pihak yang saling berhadapan. Partai yang menang dalam pemilu bertindak sebagai pemegang kekuasaan, sebaliknya partai yang kalah bertindak sebagai oposan di luar kekuasaan bertugas mengontrol kekuasaan dan memberi alternatif kebijakan kepada mereka yang berkuasa sehingga rakyat mempunyai pilihan kebijakan (Munadi, 2019).
Dalam kajian ilmu politik, istilah “oposisi” kemudian melekat pada pengertian partai politik. Surbakti (1992: 126-127) menguraikan bahwa pada negara otoriter atau totaliter, partai politik menjadi perangkat utama bagi kekuasaan untuk memproses, mengendalikan atau memperkuat kebijakan pemerintah dalam bentuk sosialisasi atau indoktrinasi kepada masyarakat untuk mendukung setiap kebijakan yang telah ditetapkan. Pada negara demokratis partai politik memiliki peran yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem kepartaian yang digunakan.
Pada negara dengan sistem dwi-partai, maka partai oposisi akan melakukan dua peran, yaitu sebagai penguasa jika memenangi pemilu dan menjadi oposisi jika kalah. Sebagai partai yang kalah dalam pemilihan umum, partai ini melakukan kontrol atas partai yang menang tetapi partai yang kalah tetap loyal terhadap sistem politik. Walaµpun berupaya keras untuk mengalahkan partai yang berkuasa tetapi tidak berupaya mengganti sistem politik yang berlaku.
Pada sistem banyak partai, partai-partai bersaing untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum. Sering terjadi pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan koalisi dengan dua atau lebih partai yang secara bersama-sama dapat mencapai mayoritas di parlemen. Untuk mencapai konsensus di antara partai-partai yang berkoalisi itu memerlukan “praktek dagang sapi”, yaitu tawar-menawar dalam hal program dan kedudukan menteri.
Dalam studinya yang terkenal, Robert A. Dahl (1982: 10-11) merumuskan adanya lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah idea politik, yaitu: (1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; dan (5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.
Menurut Dahl, kriteria yang ideal selalu menuntut berbagai hal, sehingga tidak pernah ada rezim aktual yang mampu memenuhinya secara utuh. Namun, mengingkari batasan demokrasi terhadap setiap rezim yang tidak demokratis sepenuhnya dalam artian ideal, akan sama dengan mengatakan bahwa tidak pernah ada rezim yang demokratis. Ini menjadi tidak konsisten dengan penggunaan nilai-nilai ideal lainnya seperti keadilan, keindahan, cinta dan kebijakan. Dahl menyebutkan bahwa secara historis, yang pertama kali muncul adalah rezim negara kota yang relatif demokratis. Jauh kemudian, muncul bentuk yang kedua yakni rezim negara bangsa yang relatif demokratis. Yang pertama memperlihatkan kemungkinan berlangsungnya pemerintahan rakyat dalam ukuran kecil, dan yang kedua memperlihatkan kemungkinan dalam skala lebih luas. Perbedaan di antara lembaga-lembaga politik dari kedua jenis rezim populer tersebut sebagian merupakan fungsi perbedaan dasar dalam ukuran negara kota dan negara bangsa.
Dalam penerapan demokrasi berskala luas, Dahl menyebutkan diperlukannya organisasi yang otonom bagi demokrasi per se, sebagai unsur penting dan prasyarat mutlak. Dalam hal ini, Dahl menekankan bahwa pemilihan umum tidak mungkin dapat terselenggara dalam sistem yang besar tanpa kehadiran organisasi.
Menurutnya: “Melarang partai politik akan menutup kemungkinan bagi warga untuk menyusun rencana guna menentukan dan memilih calon yang mereka sukai… Melarang semua partai politik akan memberi kesempatan istimewa pada para anggota sebuah partai tertentu dalam hubungannya dengan warga negara lainnya. Melarang para warga negara melakukan pengorganisasian yang bebas dalam rangka memperkenalkan perundang-undangan mereka kepada para pembuat undang-undang dan warga negara lainnya akan melanggar kriteria tentang partisipasi efektif dan ia akan menghina cita-cita kontrol terakhir atas agenda oleh para warga negara.” (Dahl, 1982: 60)
Bagi pluralisme demokrasi, organisasi-organisasi yang bebas sangat diinginkan dan pada waktu yang sama kebebasan dimaksud akan memungkinkannya berbuat kesalahan dan penyimpangan. Namun bagi Firman Noor, sehubungan dengan kedaulatan rakyat, oposisi menemukan relevansinya. Hal ini mengingat tidak ada jaminan jika kedaulatan rakyat dapat seluruhnya tertampung dan diterjemahkan seutuhnya oleh pemerintah.
Sejarah memperlihatkan bahwa tidak jarang pemerintahan yang mengatasnamakan kedaulatan rakyat dalam praktiknya justru menjauhi hakikat kedaulatan rakyat tersebut. Oleh karena itu, perlu kekuatan di luar pemerintahan yang dapat turut menjaga bahwa kedaulatan rakyat itu tetap ada dan berfungsi.
Dengan kata lain, eksistensi oposisi terkait erat dengan kepentingan menegakkan kedaulatan rakyat itu sendiri. Selain persoalan kedaulatan rakyat, akar demokrasi yang lain bagi keberadaan oposisi adalah partisipasi politik. Partisipasi politik sebagai prasyarat bagi eksistensi demokrasi (Pateman, 1970 sebagaimana dikutip Noor, 2016) yang dimaksudkan tentu saja bukan partisipasi yang dimobilisasi, melainkan yang independen atas dasar kesadaran individual. Partisipasi semacam ini membuka peluang bagi setiap warga negara untuk berperan sesuai dengan kesadarannya. Peluang dari kebebasan berpartisipasi ini pada akhirnya memberikan jalan bagi munculnya perbedaan sikap dan pandangan, termasuk terhadap penguasa, mengingat kesadaran setiap orang tidaklah sama
Dalam hal memahami demokrasi, ada beberapa aliran dan sudut pandang yang menjadi referensi utama untuk membahasnya. Peneliti LIPI, Firman Noor (2016) menyebutkan bahwa demokrasi dalam tatanan konseptual, setidaknya memiliki dua sudut pandang utama. Pertama adalah sudut pandang yang berfokus pada pendekatan kepemiluan atau kerap disebut minimalis. Pendekatan ini memfokuskan diri pada persoalan pemilihan umum (election) sebagai inti dari demokrasi. Bagi pandangan ini, kehidupan demokrasi tak lain adalah persoalan bagaimana berhasil dalam pelaksanaan pemilu serta ketika pejabat dan kehidupan bernegara pada akhirnya ditentukan oleh pemilu.
Pandangan kedua adalah yang melihat secara lebih maksimal, memosisikan demokrasi lebih dari sekadar pelaksanaan pemilu. Dalam sudut pandang ini, demokrasi tidak semata dilihat sebagai persoalan pemilihan umum, tetapi sebuah budaya serta ideologi yang memuat seperangkat nilai yang harus disemaikan, seperti persamaan, partisipasi, kebebasan, toleransi, keadilan, hak-hak universal, dan kesepakatan banyak orang.
Di Indonesia, pemikiran tentang demokrasi telah menjadi salah satu topik penting sejarah pemikiran politik. Eep Saefullah Fatah (1994: 14) menyebutkan bahwa para pendiri Republik —seperti Soekarno, Hatta, Soepomo dan Natsir— telah merumuskan berbagai model demokrasi yang diperuntukkan bagi praktik politik di Indonesia. Soekarno dengan falsafah sinkretismenya, Hatta dengan kekagumannya pada model sosialis demokrasi, Soepomo dengan faham negara integralistiknya dan Natsir dengan dasar-dasar ajaran Islamnya.
Fatah (1994: 14-15) menyebut bahwa keragamanan pemikiran tentang demokrasi terefleksikan dalam eksperimen demokrasi yang dijalankan selama 20 tahun pertama masa kemerdekaan. Partai politik memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan. Kompetisi antarkekuatan dan kepentingan politik mengalami masa keleluasaan terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Hingga akhirnya masa ini mengalami kehancuran setelah mengalami perpecahan antarelit dan antarpartai politik di satu sisi, serta di sisi lain akibat adanya sikap Soekarno dan militer yang menentang model demokrasi yang dijalankan.
Awal pembentukan Orde Baru, dimulai dengan apa yang disebut oleh Mochtar Loebis sebagai “Musim Semi Kebebasan”. Keruntuhan Orde Lama di akhir 1960-an ditandai dengan tumbuhnya harapan-harapan akan perbaikan keadaan sosial, ekonomi dan politik. Dalam masa yang tidak lebih dari tiga tahun, kekuasaan seolah-olah didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial politik, tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1971 dan mendukung program pembaruan pemerintahan baru.
Perolehan suara Golkar dalam Pemilu 1971 (62,8%) menjadi legitimasi politik konkret bagi pemerintahan Orde Baru yang ditulangpunggungi oleh militer. Pada saat inilah mulai terjadi kesenjangan antara negara dan masyarakat, yang ditandai oleh maraknya gelombang demonstrasi dan protes terhadap kinerja Orde Baru. Puncaknya adalah terjadinya Malari atau Malapetaka Lima Belas Januari (Fatah 1994: 19-20).
Anders Uhlin (1997: 44-45) dalam studinya tentang arus demokratisasi gelombang ketiga di Indonesia juga mencatat bahwa dominasi negara atas masyarakat menjadi ciri utama Orde Baru yang mulai menancapkan kekuasaan sejak awal 1970-an setelah mengambilalih kekuasaan dari Orde Lama pasca pemberontakan G-30S/PKI tahun 1965. Kemampuan ekonomi dan militer sangat besar. Kekuasaan negara dilaksanakan melalui patronase dan penindasan.
Orde Baru menetapkan sebuah sistem koorporatis yang disambungkan dengan wahana pemilunya, Golkar. Pengawasan negara atas masyarakat berjalan ekstensif. Campur tangan pemerintah ada di hampir seluruh wilayah kehidupan sehari-hari. Kelompok dan aktivis prodemokrasi Indonesia bekerja di bawah berbagai pembatasan yang hebat. Undang-undang tentang organisasi sosial memberikan kekuasan besar pada pemerintah untuk campur tangan dalam urusan organisasi.
Fatah (1994: 19-20) menyebutkan bahwa wajah demokrasi Orde Baru mengalami pasang surut sejalan dengan tingkat perkembangan ekonomi, politik dan ideologi sesaat atau kontemporer. Tahun-tahun awal pemerintahan Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Masa ini dikenal sebagai “bulan madu negara dengan masyarakat” atau disebut oleh Mochtar Loebis sebagai “musim semi kebebasan”. Namun prototipe demokrasi itu segera mengabur ketika bulan madu negara masyarakat menghambar. Titik tolaknya adalah kemenangan Golkar pada Pemilu 1971 yang memperoleh suara mayoritas 62,8%.
Uhlin (1997: 44-45) juga mencatat bahwa dominasi negara atas masyarakat menjadi ciri utama Orde Baru yang mulai menancapkan kekuasaan sejak awal 1970-an setelah mengambilalih kekuasaan dari Orde Lama pasca pemberontakan G-30S/PKI tahun 1965. Kemampuan ekonomi dan militer sangat besar. Kekuasaan negara dilaksanakan melalui patronase dan penindasan. Orde Baru menetapkan sebuah sistem korporatis yang disambungkan dengan wahana pemilunya, Golkar. Pengawasan negara atas masyarakat berjalan ekstensif. Campur tangan pemerintah ada di hampir seluruh wilayah kehidupan sehari-hari. Kelompok dan aktivis prodemokrasi Indonesia bekerja di bawah berbagai pembatasan yang hebat. Undang-undang tentang organisasi sosial memberikan kekuasaan besar pada pemerintah untuk campur tangan dalam urusan organisasi.
Dalam kurun waktu 23 tahun, Orde Baru melaksanakan empat pemilihan umum yang menghasilkan suatu kekuatan politik di DPR sebagai berikut: Golongan Karya (Golkar) dan ABRI meguasai kursi sekitar 70-an persen, sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya berhasil merebut sekitar 20-an persen dari keseluruhan kursi DPR yang diperebutkan. Pola kekuatan tersebut memperlihatkan bahwa Golkar dan ABRI terus menerus menguasai mayoritas suara di DPR, sedangkan PP dan PDI terus-menerus menjadi minoritas. Affan Gaffar, sebagaimana dikutip Fatah (1994: 187) menyebutkan bahwa sejak kemenangan Golkar pada Pemilu 1971, tercipta suatu sistem kepartaian yang berbeda dengan masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, yaitu The Hegemonic Party (Sistem Kepartaian Hegemonik) dengan Golkar sebagai pemegang hegomoni.
Nurcholish Madjid menggambarkan era Orde Baru sebagai berikut: Adalah karena kemantapan stabilitas… tanpa sangat terasa oleh kebanyakan orang, telah berlangsung sekian lamanya. Sebegitu jauh pengalaman akan stabilitas dalam jangka waktu tiga dasawarsa… maka stabilitas mengesankan sebagai sesuatu yang pada dirinya memang baik dan dikehendaki orang banyak. Tapi, sesungguhnya, masih terdapat ruang untuk memeriksa kembali secara serius apa sebenarnya wujud stabilitas itu yang secara hakiki menunjang usaha menyiapkan pengembangan tatanan sosial-politik yang maju di masa depan, khususnya jika dikaitkan dengan usaha mewujudkan demokrasi dan keadilan sosial”. (Madjid, 1999: 5)
Pada masa era Orde Baru, lembaga oposisi tidak diakui keberadaannya dalam struktur kelembagaan politik formal. Fatah (1994: 44) mengatakan bahwa hal inilah yang menjadikan sikap-sikap oposisional menjadi tidak terakomodasikan dalam struktur dan proses formulasi kebijakan politik.
Sebagaimana dikutip Fatah (1994: 44), Presiden Soeharto dalam biografinya mengungkapkan pandangannya sebagai berikut: Dalam demokrasi Pancasila tidak ada tempat untuk oposisi ala Barat… Tentu saja ada kontrol atas pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Kesalahan yang dibuat pemerintah harus dibetulkan. Tetapi semua harus ingat atas kesepakatan yang telah kita ambil di sini. Oposisi seperti di Barat tidak kita kenal di sini. Oposisi yang asal saja menentang, asal saja berbeda, tidak kita kenal di sini.”
Nurcholish Madjid memiliki pemikiran lain. Ia menilai bahwa oposisi penting bagi demokrasi di Indonesia karena secara filosofis, manusia tidak mungkin selalu benar. Di dalam demokrasi yang sehat diperlukan checks and balance. Yaitu, adanya kekuatan pemantau dan pengimbang. Dari sini ada istilah oposisi loyal, yaitu semangat beroposisi kepada pemerintah, tetapi loyal pada negara. Inilah yang juga membedakan antara istilah oposisi dan oposisionalisme.
Oposisionalisme itu negatif, karena dia hadir untuk menentang hanya sekedar menentang. Sifatnya sangat subyektif dan mungkin itikadnya kurang baik. Misalnya, mendaftar kesalahan orang lain. Gerakan yang muncul dalam oposisionalisme akan cenderung bersifat adhominem atau menyerang berdasarkan sisi-sisi keburukan pribadi seseorang, yang jika berlanjut akan menjadi character assassination. Oposisi loyal merupakan langkah untuk mengantisipasi munculnya oposisionalisme (Madjid dalam Dialog Keterbukaan, 1998: 6-8).
Persoalan terbesar oposisi di Indonesia adalah tidak adanya partai politik yang secara formal “berani” memainkan peran tersebut. Madjid melihat hal ini dari sisi kesejarahan, dimana memang ada peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kekhawatiran dan traumatik. Karena, proses mengalihkan kekuasaan di Indonesia tidak pernah berlangsung secara damai. Madjid pada tahun 1993 menyatakan bahwa tahun 1998 adalah mementum penting. Maka perlu dipersiapkan agar perubahan terjadi secara smooth, tidak by accident. Karena kalau gagal, maka Indonenesia akan set back. Akan terjadi peralihan kekuasaan secara berdarah. Seperti kata TB Simatupang (sebagaimana dikutip Madjid, 1998: 9), kalau gagal dalam proses pergantian kepemimpinan nasional, maka akan terjadi dengan apa yang disebut sebagai Amerikalatinisme. Di negara-negara Amerika Latin, pergantian kekuasaan dilakukan dengan cara kudeta. Dan itu bisa berlangsung berkali-kali dalam pergantian rezimnya, yang mengakibatkan harga sosial-politik yang begitu mahal).
Daftar Pustaka:
Dahl, A. Robert. 1982. Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol. Sahat Simamora (ed). Jakarta: Rajawali. Hlm. 9-10
Effendi, Edy A. (ed). 1998. Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer. Jakarta: Paramadina.
Fatah, R. Eep Saefulloh. 1994. Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia
Madjid, Nurcholish. 1999. Cita-cita Politik Islam Era Reformasi. Jakarta: Paramadina
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Cetakan ke-6 (2007). Jakarta: Grasindo.
Uhlin, Anders. 1998. Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia. Rofik Suhud (penj), Yuliani Liputo (peny). Bandung: Mizan
Munadi. Juni 2019. Oposisi dan Koalisi: Potret Kultur Demokrasi Indonesia, Jurnal Resolusi Vol. 2 (1). Materi tersedia di https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/resolusi/article/view/726, diakses 16 Januari 2021.
Noor, Firman. Juni 2016. Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi: Arti Penting Keberadaan Oposisi Sebagai Bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 42 (1). Materi tersedia di
http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/358. Diakses 8 Januari 2021.





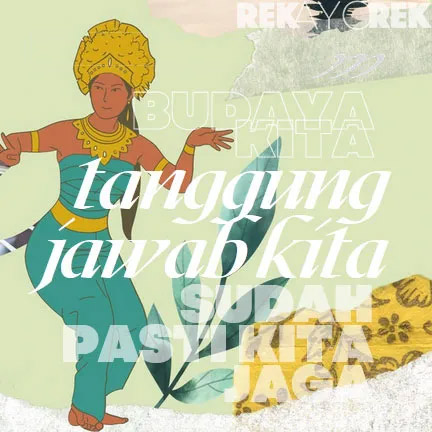






Discussion about this post